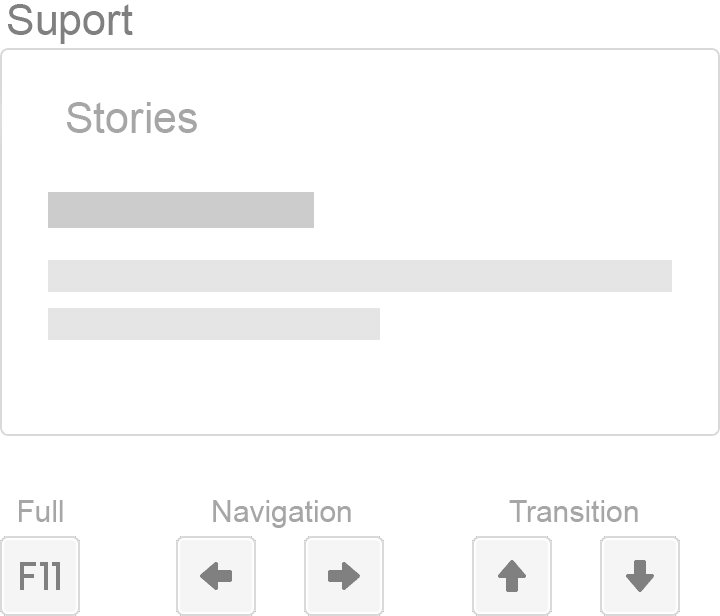Update
Rosie Pepperwhite kesal sekali. Dia kesal karena mendadak neneknya memberitahunya hal yang sama sekali tidak masuk akal. Dia juga kesal karena Catherine memberinya tugas paling bodoh—menurutnya—apalagi kalau bukan menggosok pantat kuali yang terkena jelaga. Dia pun juga kesal karena, jika benar ayah dan ibunya meninggalkannya di depan pintu untuk menyelamatkan nyawanya, dengan menitipkan anak seperti dirinya kepada wanita tua yang kesepian—siapa lagi kalau bukan Nenek, maka mereka salah besar, karena di saat-saat seperti ini, bahaya yang dibicarakan Nenek bisa saja datang.
Hal lain yang mengganggu Rosie adalah—selagi masih menggosok pantat kuali—apakah dia juga memiliki kekuatan sihir? Jika benar begitu, mengapa dari dulu dia tidak mengalami sesuatu yang menakjubkan. Yah, misalnya bisa membersihkan piring hanya dengan menjentikkan jari, atau mengumpulkan telur-telur ayam tanpa susah-susah pergi ke kandang... hal inilah yang mengganggu pikirannya. Satu hal lagi, yaitu buku warisan yang diberikan Nenek kepadanya. Sampai detik ini pun dia tak pernah bisa mengerti apa gunanya. Judulnya pun—kalau neneknya sendiri tidak tahu artinya, maka dia pun juga tidak tahu.
Rosie akhirnya menyerah untuk berpikir. Dia meletakkan kuali yang selesai digosok ke atas rak, lalu sembari menarik bagian bawah gaunnya agar tidak terserimpet tangga kayu, dia naik ke kamar. Buku tua itu tergeletak di atas tempat tidurnya. Rosie memandanginya dengan bimbang sambil duduk di dekat jendela.
"Aku tidak mengerti apa maksud Nenek memberikan buku ini padaku," katanya pada dirinya sendiri. "Mengutip kata-kata Nenek, mana mungkin aku bisa membuka buku ini, kalau aku saja tak punya kuncinya. Kalaupun aku bisa membukanya, apakah mungkin pula aku bisa membaca isinya? Bahasanya saja tidak kupahami."
Rosie mendekat mengambil buku itu, mendekatkannya sampai berjarak dua puluh senti dari wajahnya, lalu melemparnya kembali ke atas kasur.
"Rongsokan!" katanya. Lalu ia sendiri merebahkan dirinya di atas kasur, meniup rambut yang menutupi dahinya. Rosie memandangi langit-langit kamarnya dengan pandangan kosong, sebelum tiba-tiba teringat mimpinya semalam.
Pasukan berkuda... panah yang menembus baju zirah... darah di mana-mana...
Mimpi itu sekarang benar-benar jelas tergambar di otaknya. Nyaris seperti memori, tapi dengan kesamaran yang sulit dipahami. Tapi mimpi itu seolah juga nyata, seperti—seperti memori. Rosie tidak tahu harus menyebutnya apa. Bagaimanapun caranya, dia tetap bisa mengingat mimpinya kali ini. Berbeda dengan mimpi-mimpi pada umumnya, yang bisa dilupakan orang sepenggal demi sepenggal. Mimpi ini terus tergambar di pikirannya secara bertahap, lalu menghilang secara bertahap pula. Rosie mengusap wajahnya dengan putus asa.
"Aduh, kalau begini caranya aku bisa gila," dia membatin. "Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan kepadaku melalui mimpi ini?"
Tiba-tiba telinganya menangkap bunyi aneh, seperti desingan kecil. Rosie melompat dari tempat tidur, celingukan ke sana kemari mencari sumber bunyi itu.
Zzzziiiing...
Begitu bunyinya terdengar lagi, gadis itu pun kembali terlonjak. Bunyi itu ternyata berasal dari buku tua di sebelahnya. Rosie menatap buku itu dengan ngeri, lalu mundur selangkah demi selangkah hingga mencapai tembok.
Buku tua itu mendadak terjatuh dari kasur, dan sampulnya yang sudah carut-marut dimakan usia bergetar seperti menggigil. Tiba-tiba pula huruf-huruf pada sampul tua itu bergetar dan mengeluarkan cahaya kuning yang menyilaukan, lalu huruf-huruf itu melayang satu per satu, keluar dari sampul bersama cahaya menyilaukan itu. Kata-kata MAGNU WECHT OU MAGNU BOSK awalnya masih terbentuk rapi, sebelum satu per satu berpusing di tempat, lalu saling bertukar posisi, dan akhirnya tergambarlah kata-kata dalam bahasa Anglice:
GREAT BOOK FOR GREAT WIZARDS—artinya 'buku besar untuk penyihir besar.'
Rosie mengamati judul buku tersebut kembali pada tempatnya, lalu sinar yang menyilaukan itu padam. Gadis itu, masih tidak percaya, meraba bagian sampul buku. Ajaib, sampulnya yang tadinya penuh carut marut berubah menjadi mulus, seolah buku itu baru saja dibeli dari toko. Ketika jemari Rosie menyentuh gembok, buku itu kembali bergetar, lalu tulisan pada judul berpusing di tempat, membentuk kata-kata baru:
'WHAT MAKES A PAST COMES TO THE PATH, THERE IS A PAST TO KNOW THE PATH.'
Spontan Rosie mengerutkan dahi. Apa artinya kata-kata baru ini? Dia terus mengulang kata-kata dengan huruf kapital itu dengan bingung. Rupanya buku tua itu sangat baik padanya, sehingga kata-kata tersebut tidak hilang juga sebelum Rosie memahaminya.
"Aduh, tolong jangan main teka-teki sekarang, dong!" keluhnya.
"Rosie, kau di dalam kamar?" suara lantang Nurse Gwyneth terdengar dari bawah, membuat Rosie nyaris menjatuhkan bukunya karena kaget. "Apa pekerjaanmu sudah selesai?"
"Ya, Gwyneth, jangan khawatir," Rosie menyahut, "aku akan kembali ke bawah lima menit lagi. Aku—eh—aku memiliki pekerjaan yang harus kuselesaikan."
Gwyneth tidak menjawab. Mungkin dia sudah ke belakang rumah, pikir Rosie. Tapi apa, ya, maksud kata-kata misterius itu? 'WHAT MAKES A PAST COMES TO THE PATH, THERE IS A PAST TO KNOW THE PATH'—artinya 'sesuatu yang membuat masa lalu bergerak sesuai jalannya, yaitu adanya masa lalu yang mengetahui jalannya.'
Sesuatu mendadak melintas di pikiran Rosie. Cepat-cepat dia meletakkan buku kembali ke atas tempat tidur, lalu bergerak ke lemarinya dengan gelisah. Dia mencari-cari benda yang dapat membantu rasa penasarannya. Awalnya cukup sulit, karena mulanya dia lupa di mana persisnya benda itu berada. Setelah membuka semua laci dan mengangkat setiap baju, Rosie menemukannya. Benda itu tak lain adalah bola kristal biru berisi confetti putih. Ada boneka peri yang sedang menari di dalamnya. Rosie dengan gembira membawa benda itu ke dekat jendela untuk melihat bagian bawahnya.
Benda itu adalah satu-satunya sumber kenangan Rosie tentang orang tuanya. Benda itu ditemukan Nenek ketika menjemput Rosie, dan menurut Nenek, Rosie begitu menyukainya sehingga tak mau benda itu hilang. Peri di dalam bola kristal itu bisa menari dan menyanyi dulunya, lalu confetti akan berputar-putar dengan cantik. Itu dia! Mungkin itulah 'masa lalu yang mengetahui jalannya' yang dimaksud. Sampai sekarang, benda itu masih akan menjadi benda kesayangan Rosie, kalau saja dia tidak lupa di mana menaruhnya.
Yang dicari Rosie dari benda kesayangannya itu adalah cap yang mestinya ada di bagian bawahnya. Cap itu akan menjadi petunjuk di mana tepatnya benda itu dibeli, karena dengan begitu, Rosie akan lebih mudah menelusuri jejak masa lalunya. Entah keberuntungan jenis apa yang memihaknya saat ini, ia menemukan cap itu tepat di bawah tatakannya:
WINSTEAD'S.
Rosie paham, bola kristal itu pasti dibeli di toko bernama Winstead. Ia langsung merogoh ke kolong tempat tidurnya, lalu mengeluarkan selembar peta perkamen yang berdebu. Ditelusurinya nama-nama kota dan desa pada permukaan peta dengan teliti, satu per satu. Peta itu adalah besar daerah Moontrose.
Ah, ketemu, akhirnya! Dalam peta itu, tertera bahwa cabang terdekat Winstead berada di desa bernama Raventyr. Desa tempat tinggal ayah dan ibunya.
Raventyr. Entah kenapa nama desa itu membuat Rosie bergidik. Bukan hanya karena kedengarannya misterius, tapi juga karena jaraknya cukup jauh dari pemerintahan Wye Dungeon. Desa seterpencil itu pasti menjadi tempat teraman bagi orang-orang yang mau meloloskan diri dari cengkeraman prajurit kerajaan. Rosie pun kembali teringat kata-kata Nenek:
"Pergi sebelum mereka menemukanmu."
Awalnya, Rosie tidak mengerti apa maksud Nenek mengatakannya, tapi sekarang—menatap lekat-lekat nama Raventyr dan misteri yang menaunginya—Rosie merasa bahwa ia mulai memahaminya.
"Nenek ingin aku lari dari mereka," gumam Rosie pelan. Entah siapa 'mereka' yang dimaksud neneknya, tapi jauh dalam benaknya, Rosie yakin ada hubungannya 'mereka' ini dengan masa lalunya.
(***)
Rosie makan siang cepat-cepat supaya bisa mulai bekerja. Pertama-tama, dia menggali Peti Larangan-nya, lalu mengangkatnya ke kamar. Rosie juga mengumpulkan baju-baju dan beberapa saputangan, lalu mengepak semuanya di dalam ransel besar. Rosie juga memasukkan bola kristalnya diantara baju yang dilipat agar tidak terkena benturan. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, barang-barang itu sudah masuk semua ke dalam ranselnya. Hanya saja, karena dia tidak tahu caranya mengepak yang baik, ketika diangkat, ransel itu akan miring ke kiri. Namun Rosie tidak mempermasalahkan keadaan ranselnya, melainkan keadaan rumah jika dia benar-benar harus pergi.
Rosie tak mempunyai pilihan lain. Dia hanya punya satu kesempatan menggali masa lalunya, dan itu berarti pergi ke Raventyr. Hari semakin sore, dan Rosie semakin bersemangat, sampai-sampai tak bisa berhenti tersenyum saking gembiranya. Rosie merencanakan berangkat pagi-pagi buta setelah larut malam. Itu sebabnya dia menyiapkan lentera untuk menerangi jalan, sekotak korek api, dan tak lupa memasukkan juga beberapa tusuk gigi ke kantong depan ranselnya.
Makan malam berlalu dengan cepat. Setelah tidur beberapa saat, Rosie buru-buru turun dari kamarnya untuk mencari seutas tambang. Ia juga mengendap-endap ke dapur, lalu mengambil beberapa kerat roti, mengisi penuh-penuh sebuah botol minum kulit yang biasa dibawa Gwyneth dan Catherine ke ladang dengan air, serta mewadahi beberapa butir apel di dalam saputangan, lalu menjejalkan semua itu ke dalam ransel. Rosie memilih mantel bertudung berwarna merah bata yang belum pernah dia gunakan untuk bepergian, mengeluarkan sepatu bot kulit dari kotaknya. Terakhir, dia memasukkan buku tua ke dalam ransel, di tempat paling atas yang sudah dia siapkan, lalu tanpa suara keluar dari kamarnya. Sebelum mencapai pintu teras, Rosie menyisipkan surat di dekat ranjang neneknya, lalu menutup pintu perlahan-lahan. Rosie telah mencapai halaman depan ketika sosok gelap menghentikan langkahnya. Ketika sinar rembulan jatuh ke halaman, meneranginya, sosok itu ternyata Joseph.
"Joseph!" seru Rosie tertahan. "Ya ampun, kau bikin aku nyaris jantungan!"
Joseph, seperti biasa, tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan sesuatu kepada Rosie, tapi gadis itu tidak bisa melihat dalam kegelapan, sehingga Joseph mengajaknya ke pojok rumah, ke tempat yang banyak disinari cahaya rembulan. Benda yang dibawanya ternyata sebilah belati dan sebuah kompas.
"Kau memberikannya untukku?" tanya Rosie kagum. Ia tahu belati memang sangat diperlukannya untuk berjaga-jaga, dan kompas—benda itu dapat dia gunakan untuk mencari arah yang sulit. Rosie menatap wajah Joseph yang remang-remang, tiba-tiba dia merasa sedih.
"Terima kasih, Joseph," katanya. "Aku janji akan secepatnya kembali setelah berhasil menyelidiki masa laluku. Aku tidak akan pulang dengan tangan kosong."
Setelah itu, Rosie memeluk erat-erat pelayan muda itu. Ia sudah menganggap Joseph sebagai kakaknya sendiri. Rasanya berat sekali harus meninggalkan rumah seperti ini—serta orang-orang yang disayanginya, tapi dia harus melakukannya.
"Aku harus pergi, Joseph. Tempat ini tak lagi aman bagiku," katanya. "Berjanjilah bahwa kau—juga Catherine dan Gwyneth—akan menjaga Nenek baik-baik. Andaikan aku tidak kembali, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih atas jasa yang kauberikan pada kami, juga padaku."
Joseph balas memeluknya erat. Ketika melepaskannya, pemuda itu tersenyum dengan mata berbinar-binar. Setelah itu, Rosie berjalan menjauh dari rumah. Dia tak kuat menengok ke belakang, tapi melihat wajah Joseph yang masih tersenyum diterangi cahaya bulan, semangatnya tersulut kembali. Doanya mengalun dalam hati, dan dia yakin semuanya akan baik-baik saja.
Rumah-rumah di Riverway semuanya memadamkan lampu. Bintang-bintang tidak terlalu kelihatan malam itu. Udara malam akhir Oktober yang dingin lumayan menggigit. Rosie mengeratkan mantelnya sambil terus berjalan. Dia membayangkan esok hari adalah ulang tahunnya, dan untuk pertama kalinya, dia akan merayakan ulang tahun tanpa Nenek, Catherine, Gwyneth, atau Joseph. Dia tidak menyesal meninggalkan rumah, tapi air mata yang panas tak dapat dibendungnya lama-lama. Air mata itu kini mengalir deras bersamaan dengan menggelegaknya campuran rasa sedih dan bahagia dalam dadanya.
(***)
Catherine mendapati kamar Rosie kosong keesokan paginya. Dengan histeris, ia berteriak-teriak membangunkan seluruh penghuni rumah, tak terkecuali Nenek.
"Saya tidak mengerti, Nyonya," katanya sewaktu melapor. Tangisnya menjadi-jadi. "Mengapa gadis itu bisa-bisanya kabur dari rumah?"
Sang nenek hanya menanggapi laporan Catherine dengan sekilas senyum. Ia bergantian memandang Catherine, Joseph, dan Gwyneth yang duduk mengelilinginya dengan pandangan penuh arti.
"Dia tidak kabur. Dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan," jawab Nenek tenang, sembari memberi anggukan singkat pada Joseph, yang membalasnya dengan senyum samar.
"Akankah dia kembali?" tanya Catherine gemetar. "Oh, Nyonya, akankah dia pulang?"
"Aku takkan menjamin bahwa dia akan kembali lagi ke sini," sahut Nenek.
"Tapi... mengapa, Nyonya?" tanya Gwyneth, yang saat itu sama shock-nya dengan Catherine. "Di luar sana penuh penjahat dan perampok. Kalau sesuatu yang buruk terjadi padanya bagaimana?"
"Kalian bicara seolah kalian meremehkan kemampuannya," kata Nenek sambil tersenyum, "padahal kalian tahu betul siapa sebenarnya dia. Terutama kau, Catherine. Kau tahu siapa ayahnya, bukan?"
Catherine hanya bisa terdiam. Gwyneth pun tidak berani memprotes. Nenek menarik napas dalam-dalam seraya memandang ke arah jendela kamarnya, yang mengarah ke hamparan rumput luas di luar Riverway. Ia tahu, Rosie sudah memilih takdirnya.
(***)
Dua puluh sembilan hari sebelum Halloween, sebelum kejadian penyerangan keluarga Faye, bermil-mil jauhnya dari Riverway, Wye Dungeon adalah sebuah kastil megah yang terletak di pusat Moontrose. Selain sebagai pusat pemerintahan, Wye Dungeon juga merupakan jantung Moontrose, tempat kelahiran raja-raja besar. Pemimpinnya adalah Eorland Louis Harold Montrivio Daleigh yang bergelar His Royal Highness Eorland Montrivio Daleigh II atau gampangnya Raja Eorland. Namun sang raja sendiri tidak mau susah-susah dipanggil dengan 'Yang Mulia' atau 'Sire,' karena dia merasa sedikit aneh dengan panggilan itu, tapi apa boleh buat. Seluruh rakyatnya yang sudah terbiasa menggunakan panggilan tersebut tidak bisa dicegahnya.
Raja Eorland adalah putra kedua dari tiga bersaudara. Mungkin sedikit aneh bahwa biasanya yang mewarisi tahta harusnya putra pertama, tetapi kakak laki-laki Eorland, Lord Rhovanon, memilih hidup sederhana dengan mencopot gelar kebangsawanannya, lalu menikahi seorang wanita petani yang lama dia cintai. Sekarang, Lord Rhovanon bekerja di tanah Normend dan menggeluti bidang pelayaran. Hal ini mengakibatkan tahta Wye Dungeon menurun kepada Eorland, yang saat dilantik masih dalam usia muda, sekitar 25 tahun.
Sang raja sedang berjalan-jalan di balkon, menikmati udara segar di pagi hari, cuaca yang cerah, dan siulan burung yang gembira, ketika seorang pria berjanggut merah dan bertubuh tegap menghampirinya. Pria itu terengah-engah, berkeringat, dan jenggotnya berkibar di belakang selagi ia berlari.
"Ada apa, Gawain?" tanya sang raja. "Bernapaslah sejenak. Sepertinya kau tidak santai sama sekali. Ada masalah apa di luar sana?"
"Huff—huff—Yang Mulia," kata pria itu, berlutut saking capeknya. "Yang Mulia, pasukan Wye Morton dari Abbery ada di luar sana. Mereka meminta Anda keluar sekarang juga. Huff—aduh, saya sendiri ketakutan melihat wajah bengis Herbert Sang Pemberani. Kalau tidak segera ditanggapi, dia mengancam akan membakar kebun kastil."
"Herbert Sang Pemberani?" seru sang raja kaget. "Apa yang ingin dia lakukan di sini?"
"Saya tidak tahu, Sire," kata Gawain dengan terbata-bata.
Tanpa basa-basi lagi, sang raja langsung menuruni tangga yang mengantarnya menuju balairung. Rupanya, duduk di sana, sudah ada rival lamanya, Raja Herbert Sang Pemberani, yang dikelilingi para prajurit Morton. Para pengawal Wye Dungeon siap sedia dalam ruangan itu juga, tombak mereka dihunus agak tinggi. Herbert memandang angkuh Eorland seolah sang raja Dungeon itulah tamunya, bukan dia sendiri. Pria berjuluk 'Sang Pemberani' ini berperawakan gagah, tangannya berotot, dan wajahnya yang garang dipenuhi rambut gelap yang ujung-ujungnya sudah beruban. Tatapan matanya tajam dan penuh ambisi. Eorland hanya diam dengan sikap yang tak kalah angkuh, menunggu raja Morton itu menyampaikan sesuatu.
"Apakah seperti ini caramu menyambut seorang tamu, Eorland?" kata raja Morton sambil memandang aula itu berkeliling. "Tidak ada upacara meriah, tidak ada penari, tidak ada makanan, padahal kau tahu sendiri siapa aku."
"Kita semua sudah menyetujui perjanjian perdamaian itu," kata Eorland dingin. "Jadi, untuk apa kau membahas hal itu lagi bersamaku?"
"Oho-ho-ho, raja Dungeon ini memang tidak pernah berubah," kata Herbert dengan tawa sinis. "Perjanjian tetaplah perjanjian. Kalau dilanggar akan mendapat hukuman. Ya, itulah keadilan, Eorland, seperti namamu. Mereka menjulukimu 'Yang Adil,' bukan? Harusnya kau tahu apa makna dari julukanmu, seperti halnya diriku. 'Herbert Sang Pemberani,' betapa rakyat itu terlalu lugu untuk menghargai pemimpin mereka."
"Dengan demikian, apa maksudmu datang kemari, kalau bukan merusak pagi hariku yang tenang?" kata Eorland lebih tegas. "Kalau kau mau merasakan 'keadilan'-ku, maka tak sungkan pula aku mengusirmu dari tempat ini."
"Kita mulai saja dengan masalah yang sering kau sepelekan," tukas Raja Herbert. "Sekarang begini, kau ingat putri kecilku, Camelia, yang janji kaujodohkan dengan putramu sebagai bukti perdamaian? Itu semua adalah ideku, benar kan? Namun sehari sebelum ulang tahunnya, tepatnya kemarin sore, dia dibawa lari oleh seorang ksatria berjubah hitam. Pelayan pribadinya, yang bernama Ruffton, menangkap bukti bahwa ksatria itu memiliki lambang Wye Dungeon di sadelnya. Ruffton bisa saja berbohong, tapi dia adalah pelayan kepercayaanku juga, dan dia pernah berkata padaku, 'Yang Mulia, jika saya terbukti melanggar sumpah setia apalagi berbohong pada raja saya sendiri, maka saya bolehlah mati dengan dosa-dosa yang saya lakukan.' Hal ini membuatku bimbang, sekaligus terkejut—ternyata yang menculik putriku sendiri adalah orang dari negeri yang menandatangani perjanjian perdamaian denganku. Apa maksudnya semua ini, aku tak mengerti, apakah ini hanya akal-akalanmu saja untuk memperluas kekuasaan sampai Abbery, atau..."
"Cukup! Semua ucapanmu ngawur dan tidak ada bukti yang jelas!" sergah Eorland. "Aku menandatangani perjanjian perdamaian atas nama kastil, atas nama Moontrose—dan atas nama rakyatku. Sudah lama perselisihan diantara Moontrose dan Abbery menggelegak. Aku tak ingin berbuat hal yang sama dengan yang dilakukan ayahku, Herbert. Aku seorang raja, dan aku akan berpikir dahulu sebelum melakukan tindakan bodoh semacam itu."
"Ini bukan hanya terkait statusmu sebagai raja atau tidak, Eorland," kata Herbert tajam, "melainkan juga terkait wibawamu sebagai seorang pemimpin. Seharusnya kau bisa mencegah hal ini, rupanya kau membiarkannya. Apa yang tengah engkau pikirkan sehingga tega-teganya mengatakan bahwa kau tidak mendapatkan bukti yang jelas?"
"Kita semua memang memiliki banyak kekurangan," kata Eorland. "Tapi kita juga bisa menutupi kekurangan dengan kelebihan kita, dan kau menuduhku di sini—di balairung mulia—bahwa aku membiarkan putrimu dibawa lari ksatria Dungeon? Bawa keterangan fisik dan simbol ksatria itu, maka itulah bukti yang jelas. Siapa yang mempercayai seorang pelayan? Apakah dia setia atau tidak, itu bisa dibuktikan dengan sangat mudah!"
"Kau menantangku menunjukkan bukti yang jelas? Tangkaplah, aku yakin kekuatanmu sama seperti dahulu!" sang raja Morton melemparkan sebuah benda berkilauan melalui pundaknya. Eorland menangkap benda itu dengan sigap, lalu terperanjat. Benda itu adalah sebuah lencana ordo Dungeon yang terkenal—Order of Silver Shoes—dengan lambangnya sepatu bot berwarna perak.
"Dari mana kau dapatkan ini?"
"Pelayan putriku, Maybelline Ruffton, menemukan benda ini terjatuh dari sadel si ksatria yang membawa lari putriku," kata Herbert dengan suara bergetar. "Itulah, ada yang mau kaukatakan lagi, Eorland?"
Sang raja menarik napas dalam-dalam. Tatapannya putus asa sekaligus kecewa, tapi juga ada nada kasihan dalam suaranya saat ia berbicara. "Herbert, kau bukan anak muda yang berpura-pura memainkan peran seorang pemimpin kastil sembari mengenakan mahkota ayahnya. Kau adalah raja Wye Morton yang bijaksana dan dihormati rakyatnya. Begitu pula dengan masalah ini, jika memang ksatria Dungeon yang bersalah, maka baiklah, aku akan bertanggungjawab, tapi bagaimanapun juga, kau tahu undang-undangnya bahwa setiap ksatria—Dungeon ataupun Morton—berada dalam perlindungan raja, sebagaimana mereka mengabdi pada kastil. Maka dari itu, bila tuduhanmu terhadap ksatria itu salah, kau harus berhadapan denganku."
"Aku sungguh menyayangkannya, Eorland," kata Herbert, gemetar dalam suaranya begitu hebat sampai tangannya licin karena keringat. "Aku sungguh menyayangkan betapa mudahnya kau mengatakan semua itu. Aku tidak terkejut, karena putriku memang keturunan terakhir yang memegang Pearl of Palace."
Raja Eorland mengerutkan dahi. "Apa artinya itu?"
"Pearl of Palace adalah orang terhormat dari Abbery yang memegang benda paling berharga di seantero negerinya. Kau pasti lupa, karena sudah lama Raja Daleigh, ayahmu, tidak menyinggungnya, kan?" Herbert mendengus. "Yang dipegang Camelia adalah perkamen rahasia yang tersimpan di dalam locket—kalung liontinnya. Yang sekarang akan raib juga bersama dirinya. Setelah kelahiran putriku, aku mengundangmu datang ke Morton waktu itu, lalu kita membicarakan perjanjian itu disaksikan duta besar dari kedua belah pihak. Kau dengan senang hati menandatanganinya, tapi ingatkah kau apa tulisan kecil di bawah dari perjanjian itu?"
Baik wajah Herbert maupun Eorland mulai mengeras.
"Aku ingat sekarang, Herbert," kata sang raja Dungeon. "Bunyinya adalah, 'jika salah satu dari pihak kerajaan atau negeri dengan kesengajaaan atau ketidaksengajaan melanggar perjanjian yang sudah ditandatangani maka perjanjian bisa dihapus dengan dua pilihan...'"
"'Pilihan pertama, pengasingan si pelanggar dari negerinya, yang harus disetujui oleh saksi dari pihak satunya," kata Raja Herbert tenang. "atau 'pilihan kedua, mengganti rugi dengan membayar senilai dengan hak negeri lain yang dilanggar.' Terdengar ringan, bukan? Tapi kita punya satu pilihan lagi, dan para dewan sudah menyetujuinya. Mana yang kaupilih sebagai hukuman bagi ksatriamu, Eorland? Itu pun kalau dia bisa ditemukan dalam waktu dekat ini. Tapi jika tidak, berarti kau—sebagai pelindungnya di bawah undang-undang—bersedia menanggung hukumannya, bukan?"
Gawain yang sedari tadi berdiri terpaku menatap ketegangan antara dua raja itu, kini memutuskan pada dirinya sendiri untuk bergerak menjauh. Dia sama sekali tidak ingin mendengar hukuman apapun, bahkan keputusan apapun dari Eorland. Tetapi sialnya, ketika baru selangkah, hati nuraninya menyuruh dirinya mengurungkan niat.
"Aku tidak akan memilih keduanya, Herbert," kata Eorland. Terdengar bunyi kling yang berarti lencana itu terjatuh atau ada pedang yang dicabut. Gawain sama sekali tak berani memastikannya.
"Jujur saja, Herbert, aku menilai keputusanmu mengenai hukuman terdengar terlalu cepat. Ini memang murni keteledoranku, dan baik aku maupun negeriku harus menanggung malu. Tapi sikapmu itu sangat tidak layak untuk raja seperti dirimu, memasuki kastil tanpa dipersilakan, memandang rendah penguasa negeri tetangga, dan memutuskan hukuman tanpa pertimbangan—sungguh bukan sesuatu yang pantas dimiliki seorang raja. Maka itulah kenapa aku menyetujui adanya pilihan ketiga, yang akan membuktikan kesanggupan dan mempertaruhkan kehormatan kita sebagai pemimpin Moontrose ataupun Abbery. Pilihan itu berbunyi 'perang demi keadilan jika pembicaraan tak bisa diselesaikan,' namun tentu saja, perang hanya akan menghabiskan biaya, waktu, dan tenaga."
Raja Herbert memandang prajurit-prajuritnya yang diam menunggu. "Jika demikian, Eorland," katanya, "pengadilan dilaksanakan besok di pagi hari. Aku harap kau memanggil orang yang bertanggungjawab atas ksatria ini ke persidangan, tapi jika tidak, maka kau yang harus mewakilinya sendiri. Keadilan itu milik bersama, maka biarlah hukum yang menetapkannya."
Setelah berkata demikian, raja Morton itu bergegas keluar tanpa mengucapkan salam perpisahan. Raja Eorland hanya geleng-geleng kepala. Gawain yang sudah tak bisa menahan diri segera menghampiri sang raja.
"Pengadilan? Sire, kami tak bisa membiarkan buaya bangsat itu menjebloskan Anda ke penjara!" sergahnya. "Saya sudah melatih ksatria-ksatria di Dungeon selama bertahun-tahun, Sire. Jadi, biar saya saja yang datang. Saya akan mewakili Anda sebagai penanggungjawab dan pelindung ksatria."
"Tidak, Gawain. Kau tidak bisa datang," kata Eorland pelan. "Aku tidak bisa membiarkan orang-orang yang seharusnya kulindungi berada dalam cengkeraman hukuman karena kejahatan yang kita tidak ketahui sebab dan musababnya. Kau masih dibutuhkan di kastil untuk melatih putraku, jadi bila kau dipenjara, kastil akan kehilangan dirimu."
"Sire, saya pun tak melihat ada satupun harapan bila Anda harus menyerahkan diri!" seru Gawain. "Ini gila, Sire! Kastil boleh kehilangan diriku, tapi mereka tak bisa kehilangan sosok raja!"
"Gawain, kau bicara tidak ada harapan seolah-olah harapan itu benar-benar bisa kita kendalikan," kata Eorland, matanya memandang kosong ke arah pintu yang tadi dilewati Herbert dan prajuritnya. "Dungeon, Morton—kita semua sama saja. Kita sama-sama dalam masalah besar. Lagipula, apabila benar keajaiban itu ada, ia mustahil didapatkan di saat-sata genting—misalnya tiba-tiba penculik itu datang ke hadapan kita, lalu menyerahkan diri untuk dipenggal karena mengkhianati negerinya sendiri."
"Well, persetan dengan harapan, Yang Mulia—tolong maafkan perkataan kasar saya," kata Gawain, amarah dalam suaranya menggelegak. "Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya sudah lama melatih seorang ksatria—termasuk kakak laki-laki Anda—dan saya tahu betul bahwa mereka harus mengucap sumpah. Mereka harus berhati suci dan berbakti pada negeri, itulah syarat utamanya. Jika mereka tidak berhati suci, maka mereka tidak layak lulus menjadi seorang ksatria. Menurut saya, ksatria yang menculik Putri Camelia bukan berasal dari sini, tetapi sengaja mencuri lencana itu entah dari siapa—yang jelas orang itu berasal dari dari Dungeon—lalu menjatuhkannya demi menyulut kemarahan Raja Herbert kepada negeri kita. Dia tidak bisa berpikir jernih! Pasti ada yang meracuni pikirannya sehingga dia bertindak gegabah. Anda tidak boleh menanggung hukuman, Sire!"
"Well, kalau begitu berdoalah untukku, Kawan," kata sang raja seraya menggenggam pundak Gawain. Pria kepercayaannya itu, saat menatap melalui kedua matanya, langsung gemetar. Gawain tak bisa mendeskripsikan perasaannya saat itu dengan pasti. Dia juga melihat ada ketakutan di mata rajanya, yang disembunyikan guratan keriput dan alis yang tebal.
(***)
Di luar kastil Dungeon, Raja Herbert sedang sibuk berpikir. Tiba-tiba, prajurit di belakangnya berkata, "Tuanku, saya memiliki sebuah berita yang pasti Anda tak mau mendengarnya. Begini—pasukan dari Divisi Utara sudah pulang ke Morton pukul tujuh tadi pagi dan mereka menduga jejak-jejak kaki kuda yang menjauhi Abbery berhenti di Hutan Mortonwy. Mereka juga menemukan sehelai rambut wanita berwarna eboni di dahan salah satu pohon ek. Mereka akan memeriksa hutan, jika perlu membabat habis, untuk menemukan Putri Camelia. Sementara itu, Divisi Timur baru menerima berita pukul delapan. Kata mereka, di daerah Archengard ada seorang pengemis yang mengaku bertemu seorang pria asing berjubah hitam, dan pria itu membawa sebuah bungkusan di punggung kudanya. Pengemis itu baru mengalami kejadian seperti ini—bertemu seorang pria yang kasar bukan kepalang. Dia juga memberitahu bahwa pria itu meneruskan perjalanan ke Gayatown di selatan Archengard. Prajurit kita masih dalam perjalanan menyelidiki Gayatown. Itu berarti, pria yang diduga penculik itu lewat jalan pintas, karena tidak mungkin kalau dia melewati jalur Mortonwy. Terlalu berisiko baginya jika ada prajurit kita yang menemukan jejaknya."
"Terima kasih atas informasinya, Cladflaw. Aku tahu ini merupakan sebuah kejahatan yang memalukan," sang raja mendecakkan lidah. "Tsk, tsk! Aku khawatir penculik ini begitu licinnya sehingga sudah bertindak duluan daripada kita. Tapi apa boleh buat, karena pencarian kita sia-sia belaka. Putriku masih hidup atau sudah mati, entahlah—yang penting keadilan bisa berpihak pada yang benar."
Sesudah berkata demikian, Raja Herbert menatap kastil Dungeon di belakangnya dengan tangan terkepal kencang.
(***)